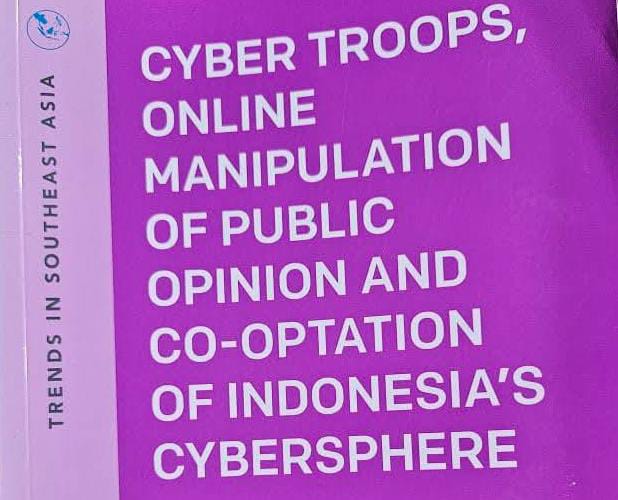Oleh : Usman Kanson
Saya pernah dicap sebagai kakak pembina buzzer ataw pendengung. Ceritanya, dalam kapasitas sebagai Dirjen IKP Kominfo, saya katakan Kominfo berurusan dengan konten, bukan orang, di satu diskusi daring pada 2022. Saya sampaikan, baik buzzer, influencer, pemuka agama, ataupun masyarakat, bila konten yang mereka produksi negatif, Kominfo bakal meminta platform men-take down. Bila buzzer, influencer, atau masyarakat memproduksi konten melanggar hukum, mereka bisa diperkarakan ke polisi. Polisi yang berurusan dengan mereka, bukan Kominfo.
Saya katakan juga Kominfo berurusan dengan orang dalam konteks literasi digital. Literasi digital mencakup masyarakat luas, tidak spesifik buzzer. Bukankah siapa pun bisa menjadi buzzer di era digital ini?
Beberapa jam kemudian muncul berita di media daring berisi omongan saya. Berita itu menyebutkan Dirjen IKP yang juga pernah menjadi Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin menyatakan Kominfo tidak berurusan dengan buzzer. Di kolom komentar ada yang menulis, “Pantes, kakak pembina buzzer rupanya…”
Komentar semacam itu, bagi saya, menunjukkan betapa jengkelnya publik terhadap buzzer. Memang apa sih salah buzzer?
Yatun Sastranidjaja dan Wijayanto melakukan studi penggunaan buzzer di Indonesia. Hasil studi mereka dituangkan dalam monograf berjudul “Cyber Troops, Online Manipulation of Public Opinion and Co-optation of Indonesia’s Cyberspace” yang diterbitkan ISEAS Yusuf Ishak Institute Singapura. Saya menemukan dan membeli monograf ini di toko buku Periplus pada 2023.
Kedua penulis menelisik penggunaan buzzer di tiga kasus: Revisi Undang-Undang KPK pada September 2019, Kebijakan Normal Baru selama Covid-19 pada Mei 2020, dan Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020.
Ringkasan studi mereka meliputi empat poin.
Pertama, manipulasi opini publik dan propaganda terorganisasi meningkat di Indonesia. Terutama sejak 2019, kampanye buzzer meningkat signifikan yang bertujuan memobilisasi konsensus publik untuk kebijakan kontroversial pemerintah.
Kedua, operasi buzzer memainkan peran penting dalam kasus kontroversial revisi UU KPK, New Normal Covid-19, dan UU Cipta Kerja, ketika publik bersikap kritis terhadap ketiga isu. Dalam ketiga kasus terang benderang terbukti buzzer memanipulasi opini publik untuk mendukung kebijakan pemerintah.
Ketiga, dalam ketiga kasus, buzzer secara sengaja membanjiri media sosial dengan narasi yang mempromosikan agenda elite pemerintahan, seringkali menggunakan pesan pelintiran dan disinformasi yang diamplifikan oleh banyak akun buzzer dan bot. Dengan begitu, buzzer efektif menenggelamkan narasi oposisi di sosial media serta pendapat berbeda dari media arus utama.
Keempat, penggunaan buzzer secara lebih sistematis mengindikasikan meningkatnya kooptasi ruang siber Indonesia untuk kepentingan elite politik.
Intinya, operasi buzzer mengancam kualitas demokrasi karena mereka tidak hanya menjejali opini publik dengan disinformasi, tetapi juga mencegah warga negara mengevaluasi dan mengkritik perilaku elite pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan.
Berdasarkan studi Sastramidjaja dan Wijayanto, kesalahan buzzer ialah operasinya yang menggerus kualitas demokrasi. Pantas saja publik jengkel dengan perilaku buzzer. Itu pula yang menyebabkan banyak media arus utama “mempersoalkan” pengangkatan seorang yang diidentifikasi sebagai buzzer menjadi staf khusus Kementerian Komdigi. (*)
●Penulis adalah mantan Dirjen IKP Kominfo RI
Editor : Harun Al Rasyid